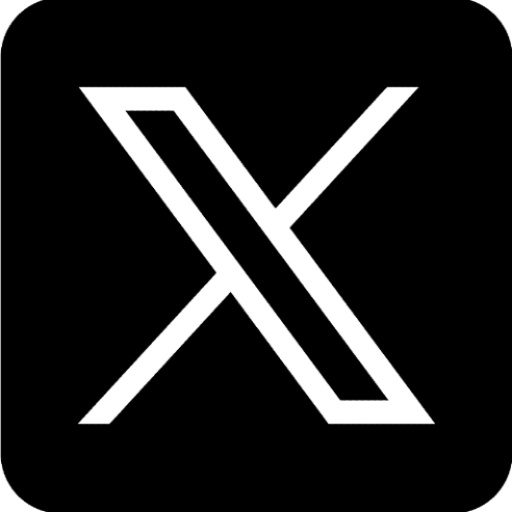Revolusi Kesehatan melalui Strategi Kebudayaan
Oleh: Setyo Budiantoro?

Agaknya kita perlu meniru Berlin yang berpenduduk kurang dari 4 juta dan mendorong budaya bergerak sejak usia dini dengan menyediakan hampir 4.000 taman bermain anak. Tidak sembarangan membuat taman bermain karena ada standar keamanan dan persyaratan tertentu agar membuat anak bergerak, berinteraksi, melatih fisik, keberanian dan kesabaran (budaya antri). Panjat besi model bola dunia, panjat tambang, perosotan, kuda goyang, ayunan dan jungkat-jungkit banyak dijumpai pada setiap sudut wilayah di Jerman. Selain menjadi sarana berinteraksi juga bagi para orang tua anak, mereka juga didorong berjalan karena taman bermain tidak terlalu jauh dari pemukiman (within walking distance) atau dalam hutan kota.
Transportasi publik yang baik dan area pedestrian yang lapang, bersih, terang dan aman di waktu malam juga menjadi kunci masyarakat bergerak. Transportasi publik yang memadai telah lama diabaikan di Indonesia, bahkan di ibukota negara. Bila tak siap mental untuk tergencet, jangan pernah mencoba kereta listrik (KRL) Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi apalagi Jakarta-Cikarang pada jam berangkat atau terutama pulang kerja.
Jalur double double track (DDT) Jakarta-Bekasi yang hanya meletakkan rel besi diatas tanah kurang dari 17 km dari tahun 2001 hingga saat ini belum selesai, nyaris 20 tahun. Bandingkan dengan Daendels yang membuat jalan Anyer-Panarukan dengan membabat hutan dan melewati bukit sepanjang 1.000 km hanya butuh waktu setahun. Akibat transportasi publik yang buruk sekitar Jabodetabek, puluhan ribu motor dan mobil membanjiri Jakarta. Tak mengherankan bila Jakarta kini menjadi kota paling terpolusi di dunia. Apakah Daendels perlu dihidupkan lagi?
Budaya Merokok
Selain physical inactivity, budaya lain yang paling merusak kesehatan adalah merokok. Budaya ini bertanggungjawab berdampak pada lebih dari 30 penyakit terutama kanker, stroke dan jantung. Bukan hal mengherankan sebuah riset menunjukkan kerugian ekonomi Indonesia akibat budaya ini mencapai Rp 600 triliun pada tahun 2015 atau 4 kali lipat dari penerimaan cukai rokok di tahun yang sama. Kerugian terutama akibat biaya kesakitan dan tahun produktif hilang karena kematian dini itu meningkat 63 persen dari dua tahun sebelumnya (Kosen, 2018).
Indonesia adalah surga para perokok karena murah dan mudah dijangkau. Jumlah perokok di negeri ini terus melesat dan menjadi konsumen rokok terbesar ketiga dunia. Bahkan memecahkan rekor dunia, kini sekitar 70 persen laki-laki dewasa Indonesia adalah perokok. Yang jauh lebih merisaukan lagi, selama 8 tahun (2005-2013) perokok berusia 10-14 tahun meningkat hampir 10 kali lipat. Tahun 2014, remaja usia 13-15 tahun sekitar 20 persen adalah perokok aktif dan remajaaki mencapai 35 persen.
Hal yang lebih mengenaskan terjadi pada balita yang memiliki orang tua perokok. Disamping berpotensi menjadi korban perokok pasif, riset memperlihatkan balita tersebut memiliki kecenderungan besar mengalami stunting (Dartanto, 2018). Seperti dijelaskan di depan, stunting menggerus kemampuan kognitif dan kapabilitas manusia. Artinya, nilai kalkulasi kerugian Rp 600 triliun akibat konsumsi rokok sebenarnya terlalu konservatif. Perilaku merokok telah menjadi tsunami senyap (silent tsunami) kesehatan dan kerugian fiskal yang dahsyat.
Di samping kenaikan harga rokok untuk melindungi kesehatan sekaligus meningkatkan pendapatan negara, salah satu hal paling moderat mengendalikan konsumsi rokok adalah melarang iklan rokok. Pelarangan ini tidak akan mengurangi jumlah konsumsi rokok, namun terutama hanya membatasi anak mulai merokok. Industri rokok padat karya skala kecil dan menengah justru akan lebih diuntungkan karena sebelumnya tak bisa bersaing membuat iklan. Petani tembakau Indonesia juga diuntungkan karena industri kecil dan menengah tersebut bisa dipastikan akan mengkonsumsi produksi mereka.
Untuk kebutuhan nutrisi bagi masyarakat secara umum, Indonesia tidak memiliki panduan memilih makanan yang memadai. Panduan makanan justru berasal dari iklan, terutama televisi.
- Kemnaker Berkolaborasi dengan BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja
- Sosialisasi Empat Pilar MPR di Banjarbaru, Habib Aboe: Stunting Harus Dilawan
- Teken MoU, BKKBN dan Otorita IKN Siap Jadi Contoh Tidak Melahirkan Stunting Baru
- Dorong Gerakan Hidup Sehat Dilakukan Secara Masif, Lestari Moerdijat Khawatir Soal Ini
- Kasus Stunting di Bangka Selatan Alami Penurunan
- Pemkab Tabanan Sukses Turunkan Angka Stunting Menjadi 6,3 Persen
 JPNN.com
JPNN.com