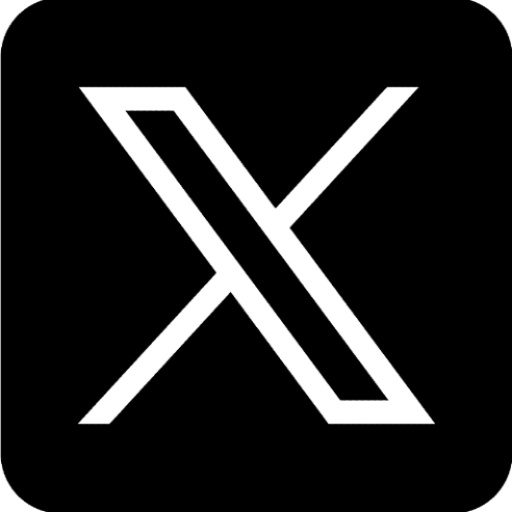Wayang
Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Anderson melihat pengaruh yang kuat antara mitologi wayang dengan sikap orang Jawa yang terkenal toleran dan moderat. Budaya moderasi Jawa diwarnai dengan sikap "nerima ing pandum", menerima apa yang menjadi bagiannya, dan sikap "sak derma ngelakoni", hanya menjalankan peran yang sudah ditetapkan.
Dengan filosofi ini orang Jawa harus patuh dan tunduk kepada pimpinan, yang mendapatkan wahyu kedaton yang punya dimensi ilahiah. Raja atau pemimpin adalah wakil Tuhan di bumi, dan rakyat atau abdi harus patuh sebagai bagian dari kepatuhan kepada Tuhan.
Pemimpin Jawa harus manunggal dengan rakyat sebagai pengejawentahan konsep "manunggaling kawula gusti", menyatunya rakyat dengan pemimpin, menyatunya abdi dengan tuhannya.
Karena itu manusia Jawa tidak mementingkan kebutuhan pribadinya, tetapi lebih mengedepankan keutuhan kolektif. Hak-hak individu melebur ke dalam hak-hak kolektif di bawah kepemimpinan sang raja.
Ketika para bapak bangsa, the founding fathers Indonesia berdebat mengenai dasar negara, muncul argumen yang mendukung gagasan individualistik dan gagasan masyarakat kolektif.
Mr Soepomo mengajukan konsep masyarakat kolektif, yang memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk menjadi representasi rakyat dalam mengambil keputusan strategis.
Jean Jaques Rosseau menyebutnya sebagai "general will" kehendak umum yang diwakilkan kepada sejumlah elite pemimpin. Soepomo mendasari pandangannya pada filosofi "manunggaling kawula gusti", tetapi Marsillam Simanjuntak menyebut filosofi itu sebagai fasis.
Pada masa Orde Baru, Soeharto mengeksploitasi filosofi wayang menjadi dasar-dasar filosofi politiknya. Hak-hak individualistik ditiadakan, dan diintegrasikan menjadi hak kolektif yang diwakili oleh pemimpin yang ditunjuk oleh wakil rakyat.
Pasopati yang menjadi andalan Arjuna membelah dada Karna. Arjuna menangis. Karna mati dengan tersenyum.
- Memaknai Peperangan di Padang Kurusetra Dalam Epos Mahabarata
- Pesan Megawati di Acara Wayang, Hasto: Tahun Ini, PDIP Menghadapi Vivere Pericoloso
- Sosialisasi Empat Pilar MPR, Lestari Moerdijat Hadirkan Pertunjukan Wayang Kulit
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- KPK Panggil Bos PT Kereta Api Properti Manajemen
- Belangkon Merah
 JPNN.com
JPNN.com