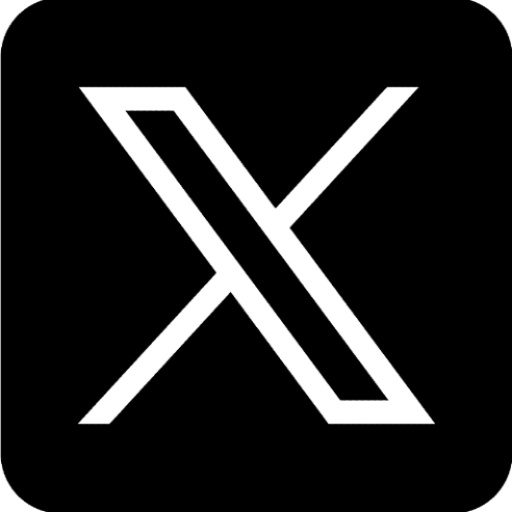Bangsa Tempe
Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Sebagaimana prinsip dalam ‘’The Animal Farm’’ Orwell, ‘’All animal area created equal, but some are more equal than others’’; semua hewan diciptakan setara, tetapi beberapa hewan punya kesetaraan lebih tinggi dibanding lainnya.
Itulah paradoks kesetaraan. Indonesia tahu dan sadar diri bahwa sebagai junior partner tidak mungkin menuntut kesetaraan yang lebih tinggi yang dinikmati oleh negara-negara senior partner seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara Uni Eropa.
Rasa tahu diri itu kita terima sebagai bagian dari hegemoni.
Dengan penuh rasa tahu diri Indonesia melakukan konformintas, penyesuaian diri, dengan aturan-aturan yang sudah disepakati organisasi. Negara-negara anggota harus menjadi negara yang terbuka terhadap perdagangan internasional, ramah terhadap investasi asing, dan terbuka terhadap aliran modal.
Untuk menjamin konformitas itulah Indonesia menciptakan Omnibus Law demi menjamin berlangsungnya aturan main yang sudah disepakati bersama. Globalisasi menjadi permainan bersama yang dirayakan bersama dengan penuh kegembiraan dan sukacita.
Itulah yang bisa menjelaskan mengapa Indonesia yang menjadi salah satu produsen terbesar kelapa sawit dunia tidak bisa mengontrol harga minyak goreng di dalam negeri. Kita yang punya kelapa sawit, tetapi kita tidak bisa mengatur harganya. Semua didikte oleh mekanisme pasar internasional berdasarkan prinsip ekuilibrium pasar dalam mekanisme ‘’the invisible hand’’.
Ketika kita menyaksikan ratusan ibu berdesak-desakan saling sikut berebut minyak goreng, ketika kita menyaksikan ratusan orang mengantre dengan sabar untuk mendapatkan jatah minyak goreng murah, di situlah kita mendapatkan gambaran mengenai penjajahan modern dalam bentuk hegemoni.
Bangsa Indonesia menikmati tempe secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya kuliner yang sudah menjadi milik bangsa selama berabad-abad. Ketika tempe kemudian menghilang karena para perajin melakukan boikot, kita pun tersadar bahwa untuk mempertahankan keberadaan tempe pun kita tidak cukup punya kekuatan.
Sebutan bangsa tempe yang dibuat oleh Bung Karno terasa sangat ironis sekarang. Rasanya kita ini memang bangsa tempe yang lembek.
- Berkat BNI Xpora Produsen Tempe Asal Bogor ini Bisa Tembus Ekspor ke 10 Negara
- 5 Khasiat Kacang Kedelai, Bantu Turunkan Serangan Penyakit Ini pada Pria
- Asosiasi Kedelai Indonesia Siap Dukung Ketahanan Pangan Nasional
- Dukung Kemajuan UMKM Lokal, FKS Group Beri Pembinaan untuk Perajin Tempe
- 5 Manfaat Kacang Kedelai, Bikin Pria Makin Betah di Ranjang
- Warpong Buan Tawarkan Ponggol Istimewa & Kekinian
 JPNN.com
JPNN.com