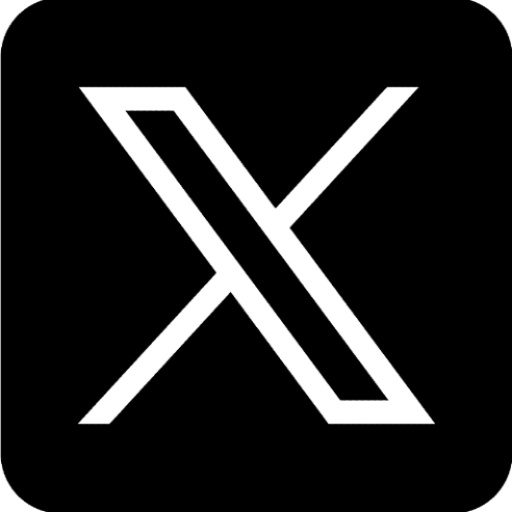Solo: Sebuah Barometer
Jumat, 24 Mei 2013 – 17:01 WIB

Solo: Sebuah Barometer
LIMA belas tahun yang silam, pasti sulit untuk membayangkan apa yang telah saya saksikan di Solo pada minggu lalu. Saat itu – dalam dua hari antara 14-15 Mei 1998 – Solo tak ubahnya Jakarta yang membara dilalap api. Di luar pintu masuk, terdapat kebisingan yang ditimbulkan oleh promosi produk minyak goreng dengan hiburan penyanyi dan band. Saya tidak bisa melihat siapa penyanyinya, tapi jika menilai dari suaranya yang kuat, ia tentu orang yang enerjik dan lengkingan suaranya lama-kelamaan membuat kepala saya pening.
18-19 Mei kemarin saya menghabiskan akhir pekan di Solo, lima belas tahun kemudian beranjak dari tahun 1998 – kota di Jawa Tengah ini telah berubah. Alih-alih puing-puing bangunan yang tersisa (yang sebagian besar dimiliki etnis Cina), kota ini sekarang disesaki dengan pembeli dan wisatawan yang tertarik mengunjungi situs sejarah, studio pengerjaan batik, serta menjajal panganan khasnya – yang jelas merupakan bagian dari sejarah.
Baca Juga:
Solo menjadi bagian dari cerita klasik pada masa transisi Indonesia. Saya berdiri tepat di Jalan Slamet Riyadi yang menjadi pintu utama ke Solo Paragon, salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan terbaru di kota ini. Pengunjung ramai keluar masuk. Terdiri dari dua lantai yang dilengkapi dengan Carrefour dan Centro, Solo Paragon menarik pengunjung untuk berbelanja dan melakukan banyak hal, terlebih karena berbagai restoran dan kafe yang bertebaran juga dipenuhi oleh pengunjung.
Baca Juga:
 JPNN.com
JPNN.com