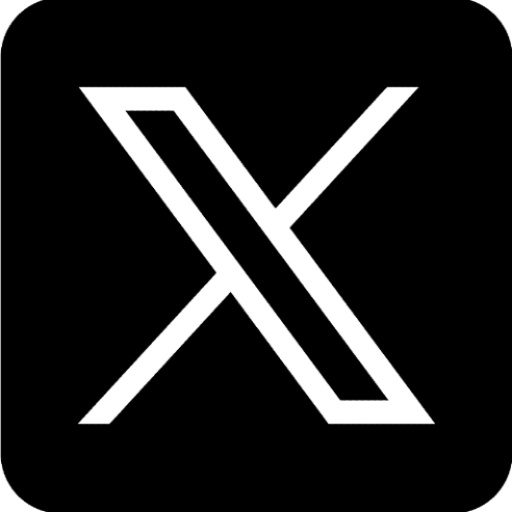'Keinginan Luhur' Politisi
Oleh; Ichsanuddin Noorsy*

jpnn.com - “INI Indonesia ya,” kata saya merespon diskusi terbatas di grup BBM Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) tentang kampanye pilpres yang sudah “membelah” masyarakat Indonesia. Itu sikap trenyuh mendalam menyaksikan keterbelahan anak bangsa Indonesia menyusul kampanye calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (PS-HR) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JS-JK).
Saya teringat di awal reformasi. Begitu derasnya desakan meliberalkan segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud keinginan berobah dari era sentralistik dan otoriter. Saking kuatnya desakan itu, amandemen UUD 1945 yang dilakukan dengan empat kali peruabahan pun tanpa melakukan kajian akademik mendalam. Elite menghendaki perubahan dan rakyat luas tidak mengetahui dan memahami ke mana arah perubahan itu.
Pada 2001 saya menulis di sebuah koran nasional bahwa hasil empat kali amandemen itu adalah rancunya batang tubuh dan lahirnya tujuh masalah inkonsistensi UUD 2001. Salah satu masalah itu adalah apa yang sedang dihadapi bangsa ini sekarang: perebutan kekuasaan di elit politik yang melahirkan potensi konflik horizontal di berbagai lapisan masyarakat.
Adakah hal seperti ini yang dikehendaki para pejuang kemerdekaan Indonesia dan para pendiri republik? Tanpa harus menoleh sejarah terlalu jauh dan mendalam, kita mendapat jawaban, “Tidak.” Para pendiri republik dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan bangsa itu berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur agar kehidupan berbangsa bebas tertindas (dengan segala bentuk ketertindasan).
Tentu termasuk tertindas dalam alam pemikiran. Begitu kurang lebih bunyi alinea ketiga di Pembukaan UUD 1945.
Sejak reformasi, saat parpol diamanatkan dalam amandemen keempat UUD 2001 sebagai satu-satunya kendaraan untuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka berbagai kalangan mendirikan parpol. Pada beberapa aspek, hal ini positif karena mungkin saja agregasi aspirasi masyarakat tidak tertampung pada parpol yang ada. Dalam perkembangannya, disadari juga bahwa kebebasan mendirikan parpol melahirkan dampak negatif. Misalnya hanya dijadikan ajang mendulang uang dan membuka akses kekuasaan. Sementara akses kekuasaan pun digunakan untuk meraih kekayaan bagi petinggi parpol.
Dampak negatif lainnya, masyarakat digiring menurut kepentingan parpol, padahal kepentingan tertinggi masyarakat adalah tegak dan terlaksananya UUD 1945 sesuai dengan amanat dan cita-citanya. Untuk menggiring keputusan masyarakat, maka digunakan industri survei guna mempengaruhi opini publik. Di AS, industri survei -disertai dengan model kampanye yang membuka kejelekan lawan dan saling menihilkan- tumbuh subur bersamaan dengan perusahaan-perusahaan lobbi yang juga bertugas mempublikasikan kehebatan klien sembari mencari kelemahan lawan.
Karena prinsip no free lunch dalam rujukan nilai kebebasan individual, untuk Indonesia saya menyebutnya sebagai demokrasi korporasi sejak Pemilu 2004. Yakni suatu demokrasi berdasarkan transaksi materi yang pembiayaannya bersumber dari korporasi. Inilah politik uang.
“INI Indonesia ya,” kata saya merespon diskusi terbatas di grup BBM Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) tentang kampanye pilpres
- Zakat dan Pemberdayaan Pekerja, Mengapresiasi Gebrakan Presiden Prabowo di Hari Buruh
- Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan dengan Negara Lain
- 'Indonesia First’ demi RI yang Berdikari di Tengah Gejolak Dunia
- Prabowo Subianto dan Relasinya dengan Umat Islam
- Wacana Gelar Pahlawan untuk Pak Harto dan Bagaimana Menyikapinya
- Halalbihalal UNTAR 2025 Merajut Harmoni, Menyongsong Kemenangan dalam Keberagaman
 JPNN.com
JPNN.com